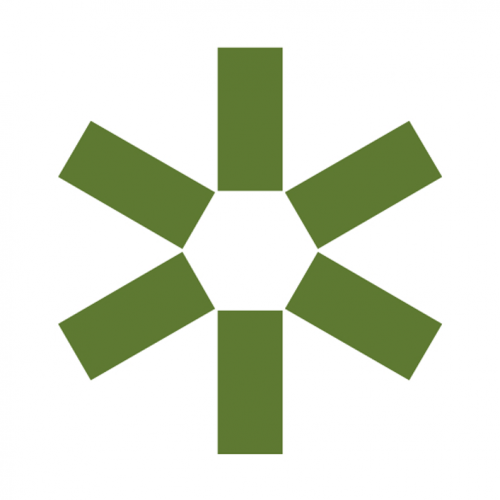Rombongan Mapala UI berhasil menaklukkan puncak tertinggi Amerika Utara. Ketemu sosok misterius. Tantyo Bangun, Project Officer pendakian menuliskan khusus untuk Matra (November 1989).
Norman keluar, diikuti Didiek, Deddy, dan Sute. Keempatnya melongok kiri dan kanan. Putih semua. Mata mereka mencari-cari perlengkapan pendakian yang terkubur hujan es semalam suntuk. “Huh… Tabiat asli Denali baru kelihatan. Kemarin-kemarin masih
tenang, hari ini mengamuk…” catat Didiek di buku hariannya. Denali adalah nama asli gunung McKinley. Dalam bahasa Indian Athabasca, Denali berarti Yang Tinggi. Hari itu adalah hari keempat pendakian. Mereka kini berada di ketinggian 3.165 meter sesudah Kahiltna Pass.
Memang, hari-hari pertama mereka menyapa Denali disambut dengan sopan. Cuaca begitu bagus sejak mereka meninggalkan kemah induk di Kahiltna Glacier, 2.195 meter. Akhir musim panas yang biasanya diwarnai dengan angin kencang di Alaska tak terlihat. Ketinggian demi ketinggian bertambah. Kesulitan hanya timbul dari masalah teknis kecil.
Sute, misalnya, harus sering terjatuh sebelum Kahiltna Pass. Kikuknya belum hilang dengan cara berjalan menggunakan snow shoe. Penyesuaian langkahnya keliru. Seharusnya, ia lebih banyak melangkah dengan menggeser telapak kakinya. Namun ia melangkah dengan langkah lebar, bak pria habis dikhitan. Snow shoe-nya yang lebar sering mengganjal. Terjungkallah dia. Memang tak mudah berjalan di salju dengan budaya Eskimo.
Halangan lain yang menimpa Sute adalah kesehatannya. Tak tahu kenapa, kondisi anak Sastra Prancis yang pendiam ini jadi menurun. Norman menulis di laporan pendakiannya: “Perjalanan terhambat karena Sute merasa pusing-pusing dan terpaksa berhenti. Sementara di kiri-kanan banyak sekali crevasse (jurang es).”
Didiek lain lagi masalahnya. Sepatu saljunya seringkali lepas. Untuk membetulkan dalam kondisi biasa mungkin tidak masalah. Tapi ia ada dalam tim. Satu orang berhenti, yang lain akan ikut berhenti. Norman yang biasanya tidak kenal kompromi, saat itu bersikap lain. Berkali-kali sled Didiek dihelanya mendaki lereng terjal. Dan rombongan “kura-kura” itu dapat mendaki sedikit lebih cepat.
Kahiltna Pass mereka lewati. Lereng salju semakin terjal. Sekali-kali mereka menengok ke arah Mount Foraker, “istri” dari Denali. Cuaca buruk terlihat mendatangi. Untuk yakinnya, Deddy dengan lensa panjang melihat puncak Denali. Benar, Lenticular Caps yang terbentuk dari hamburan es yang tertiup badai tampak menyelimutinya. Tak ada pilihan lain kecuali berhenti.
Deddy dan Didiek mengeluarkan sekop salju. Mereka harus menggali salju lebih dalam. Tenda harus tertanam lebih banyak untuk dapat menahan serangan badai. Hanya ujung atapnya saja yang boleh terlihat. Setengah jam menggali, selasai sudah bunker salju mereka.
Jam delapan malam badai menghantam mereka. Terus-menerus menderu. Kain tenda yang membeku karena tiupan badai berderak-derak suaranya. “Pertama-tama McKinley adalah gunung sub-Arctic. Udara ‘terhangat’ pada musim dingin adalah minus 40 derajat celcius, dengan rekor kecepatan angin 40 kilometer per jam,” begitu tulisan Bradford Washburn, Direktur Boston Museum of Science, kembali terlintas dalam benak mereka.
Washburn orang yang pertama kali membuka rute West Buttress pada tahun 1953. Ia, waktu itu, dihantam badai pada posisi yang sama dengan para pendaki Indonesia sekarang. Pendaki Jepang, pada beberapa tahun lalu juga terhantam di sini. Nasib buruk menimpa mereka. Mereka hilang disapu angin. “Fakta-fakta itu, terus terang membikin kami terjaga sepanjang malam,” tutur Didiek. McKinley malam itu memang sungguh menakutkan.
Syukurlah, ketakutan mereka tidak berkepanjangan. Di Jakarta, pukul setengah empat dinihari tanggal 11 Juli, mereka mengabarkan hal ini: “Sukses! Kami sudah sampai dengan selamat di Puncak McKinley tanggal 7 Juli. Nggak kurang sedikit pun. Pokoknya normal.” Itu kata-kata pertama dari facsimile yang kami tunggu-tunggu. Hilang semua kepenatan selama delapan bulan terakhir.
Memang, persiapan matang akhirnya menentukan. Mereka mendaki dengan cepat. Malah boleh dibilang terlalu cepat. Saya ingat telepon Didiek dari Talkeetna, beberapa saat sebelum terbang ke kemah induk di Kahiltna Glacier, “Sampai tanggal 22 Juli kami ada di McKinley. Kira-kira pendakian akan makan waktu tiga minggu.”
Ternyata tanggal 11 Juli mereka sudah di bawah lagi dan berhasil. Hasilnya memang di atas rata-rata. Pendakian tercepat di McKinley, sejak diresmikan menjadi taman nasional, tercatat 9 hari dan pendakian terpanjang 24 hari. Orang-orang tropis Indonesia ini baru pertama kali mencoba membukukan waktu 10 hari. Saya lalu teringat awal semua petualangan ini.
Waktu itu, dalam pertemuan di Jakarta, 29 Oktober 1988, semua yang hadir sibuk berdebat. Adi Seno dengan segala pengetahuannya tentang gunung salju di seluruh belahan bumi membeberkan pandangannya. Saya bersama Sulis, Eka dan Makky mendengarkan dengan antusias. Adi mengajukan usul sasaran ekspedisi berikutnya, setelah cukup berhasil menapaki pegunungan Andes pada bulan Juli.
“Yang paling mungkin memang McKinley. Ia layak dijadikan sasaran antara sebelum kita kembali ke Himalaya, atau meneruskan program “seven summit”, pendakian ke tujuh puncak tertinggi di tujuh benua.” Kata Adi membandingkan Denali (McKinley) dengan kandidat lain, seperti Makalu (Nepal) dan Aconcagua (Argentina).
“Pat (Morrow) juga menyiapkan diri ke Everest dari McKinley dan Aconcagua. Sesudah itu baru puncak lainnya,” Adi menambahkan. Pat adalah rekan pendaki asal Kanada yang telah mencapai seven summit.
Rapat Badan Khusus Ekspedisi Mapala Universitas Indonesia hari itu selesai. Keputusannya secara bulat menetapkan Gunung McKinley sebagai sasaran tahun ini. Gunung itu menjulang menjadi titik tertinggi di Alaska. Letaknya yang 390 kilometer dari lingkaran Artik, menawarkan medan yang tidak bersahabat. Dan saya mendapat tugas berat untuk menjadi project officer-nya.
Setelah saya pikirkan selama seminggu, akhirnya saya terima tawaran itu. Sebab tugas itu punya banyak konsekuensi. Misalnya, harus menunda skripsi, menahan diri untuk tidak bisa ikut ekspedisi ke Irian, dan mengurangi perhatian ke masalah keluarga. Yang paling berat adalah mengatur sejumlah ego untuk bekerja bersama mencapai puncak McKinley.
Mengatur masalah ego ini dituntut kepintaran tertentu. Dengan tenaga yang ada sekarang, terus terang kepercayaan terhadap kemampuan teman-teman untuk sampai ke puncak McKinley tidak diragukan. Mula-mula tiga belas orang yang mendaftar seleksi. Tapi akhirnya terpilih empat orang. Semuanya cukup handal, dan “jam terbang” mereka lumayan panjang. Tapi rasanya ada yang kurang. Saya butuh motivator.
“Kenapa tidak mengajak Norman?” pertanyaan setengah usul dari Sulis.
Norman Edwin. Terbayang di kepala saya sebuah ego lain yang sangat dominan. Saya teringat pengalaman hitam dengannya. Tragedi Ekspedisi Arung Jeram Sungai Alas melintas kembali. Kami kehilangan Mas Budi Belek dan Tom Sukaryadi waktu itu. Jeram-jeram ganas sungai Alas mengalahkan mereka. Saat itulah saya melihat – untuk pertama kalinya – orang sekeras Norman bisa menangis. Tapi itu jelas bukan tangisnya yang pertama jika kehilangan teman dalam ekspedisi.
Tahun 1981, Norman juga menangis waktu mendengar Hartono Basuki meninggal di dinding Selatan Carstensz Pyramid. Saat itu ia yang menjadi ketua ekspedisinya. Walaupun secara teknis ekspedisi itu sukses, dengan korban satu nyawa tak urung Norman sempat “diadili”.
Pengalaman-pengalaman itu membuahkan anekdot-anekdot. Teman-temannya bilang kalau ia bertualang, pulangnya selalu membawa peti (mati). Di sisi lain dengan keberuntungannya yang tinggi, mereka berkomentar bahwa ia punya nyawa cadangan.
Tapi orang yang satu ini benar-benar fenomena kepribadian yang unik. Orang mungkin berpendapat, semangat egaliter yang sangat ditanamkan dalam keseharian di Mapala, membentuk pribadi-pribadi yang semau-maunya. Bebas. Dan paling buruk: tidak mengenal disiplin. Memang itu yang terjadi. Tapi ada nuansa lain juga dari pergaulan dengan alam.
Orang yang belajar dari alam tidak mengenal larangan. Namun siapa yang ceroboh, hukumannya adalah maut. Ini kalimat kunci dan itu yang menyebabkan terbentuknya kepribadian “tanpa larangan, tapi siap menanggung risiko”. Norman tak terkecuali.
Rambutnya gondrong berkuncir. Lelucon-leluconnya selalu menyerempet-nyerempet porno, dan hanya memiliki satu kemeja di antara seluruh T-shirtnya. Semuanya berkesan urakan. Tapi ada faktor yang berlawanan. Semangat hidupnya kadang terasa kelewatan.
Waktu pertama mendapat tawaran itu, sambutannya baik. “Tapi gua mesti ke Sulawesi dulu, barang sebulanlah,” begitu katanya. “Kalau bisa gua sudah dapat referensi yang mesti dibaca.”
Saya lalu menyodorkan Surviving Denali. “Problem paling besar menghadapi frostbite (sengatan dingin). Artinya perlengkapannya harus ultra ekstrem untuk bisa lewat di kondisi minus 40 derajat Celicius,” kata saya menjelaskan.
Anggota tim sudah terseleksi. Didiek Samsu sebagai orang kedua setelah Norman. Didiek dengan pengalaman Himalaya dan Andes punya cukup disiplin. Walaupun tulisannya seperti cakar ayam, pengaturan administrasinya cukup rapi. Dan yang penting ia dapat bekerja di bawah pimpinan Norman. Sarjana arkeologi ini bertekad hidup dari bergiat di alam bebas.Ini langka di sini, tapi saya butuh orang seperti itu. Saya tidak senang dengan orang yang setengah-setengah.
Personil lainnya adalah Deddy. Si “easy going” yang sangat menelantarkan kuliahnya di fakultas sastra ini bisa cocok untuk ekspedisi McKinley. Pengalaman saya bersamanya mendaki di Chimborazo, Andes memang menyiratkan apa yang perlu saya ketahui tentang dirinya. Untuk kepemimpinan memang Deddy tidak terlalu menonjol, tetapi sebagai pasukan komando, tidak pernah ada kata “tidak bisa” dalam kamusnya.
Deddy sangat jarang marah. Kalau marah pun mudah ketahuan. Ia akan menyendiri dan diam. Ini sikap marah yang “bagus”. Artinya tidak merusak ekspedisi dengan mengamuk dan mengomel tanpa kejelasan.
Anggota terakhir adalah anak paling muda dari kami. Sugihono Sutedjo. Ia meroket dengan cepat sebagai pendaki, dan mematahkan mitos bahwa anak sastra Perancis harus lemah lembut. Tahun 1987 ia masih anak bawang. Tapi dengan cepat ia belajar dan belajar. Januari lalu ia memimpin rekan-rekannya menaklukkan Mount Cook, gunung tertinggi di Selandia Baru.
Saat tengah menyeleksi tim McKinley, satu keputusan besar lagi saya buat. Saya memutuskan untuk tidak ikut. Saya merasa ini yang terbaik untuk tim. Dengan usaha fund raising selama enam bulan sudah cukup menyita waktu. Ditambah lagi persiapan fisik dan teknis untuk mendaki gunung dengan tingkat kesulitan seperti McKinley, sungguh di luar kemampuan.
Tim sudah ada, masalah belum terpecahkan. Orang-orang ini tetap punya ego yang sangat besar. Dalam stress berat bisa timbul konflik yang bisa merusak tim. Memikirkan bagaimana cara menyelaraskannya, saya bicara dengan beberapa psikolog. Saya tanyakan baiknya suatu program latihan. Mereka setuju dengan usul saya untuk mengumpulkan tim ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Paling tidak mereka terbiasa mengenal kepribadian teman seperjalanan ke Puncak McKinley. Saya satukan di rumah Norman selama dua bulan.
“Ini perlu untuk tim. Bayangkan saja beda usia gua dengan Sute sekitar tiga belas tahun. Dan dia entar jadi satu tim yang harus gua anggap punya kemampuan rata dengan lainnya. Paling tidak dia tidak usah sungkan sama gua. Jangan mentang-mentang gua lebih tua, Sute nggak berani menegur kalau gua salah. Kalau di McKinley bisa jadi bahaya.”
Kalau dari referensi Barat memang agak lain. Pendaki terkenal macam Reinhold Messner, Chris Bonington, Doug Scott, Lou Whittaker tidak memerlukan model seperti ini. Mereka profesional disitu. “Kerja”nya memang naik gunung. Paling tidak usia mereka pun matang.
Persiapan teknis mulai berjalan. Lari 10 kilometer sehari, latihan beban 3 kali seminggu, memanjat dan mendaki pada akhir minggu. Semua memang berat dan membosankan. “Camping dong sekali-sekali,” pinta Deddy.
Permintaan Deddy terkabul, saya aja mereka camping di dalam Cold Storage. Semalam berlangsung dengan aman. Suhu di awal kami masuk hanya 20 derajat di bawah nol. Makin lama perlahan merayap turun sampai titik minus 40. Kamera video 8 mm yang saya coba untuk mengabadikan mereka hanya bertahan lima menit. Baterainya ngadat membeku. Tapi hasil simulasi di Cold Storage ini banyak. Semua merasa siap untuk berada lebih lama di kebekuan itu.
Tapi ada halangan kecil lain. Dokter Dangsina Moeloek, pengamat medis tim ini menemukan bahwa Hb darah mereka turun setelah tes faal yang ketiga. “Pendaki gunung harus punya Hb tinggi. Di ketinggian oksigen susah diangkut ke otak kalau Hb rendah,” kata dokter Dangsina,“tapi saya akan cek ke PMI, apakah sesuai dengan kondisi Indonesia.”
Jawabannya positif, ternyata darah mereka masih lebih baik dibanding dengan kondisi darah rata-rata orang Indonesia. Saya kurang puas. Kami lakukan simulasi ketinggian di Lakespra Saryanto. Hasilnya bagus, saya puas.
Ekspedisi McKinley masuk tahap in action. Didiek dan Sute berangkat lebih awal seminggu. Di Anchorage mereka akan belanja di REI. Mapala UI tercatat sebagai member di sana. Paling tidak bisa dapat potongan. Tiap orang rata-rata menghabiskan biaya sebesar 4.000 dollar untuk perlengkapan pendakian di suhu ekstrem dingin. “Soal perlengakapan kami dipuji oleh pendaki lain. Untuk Alpine tacic memang tidak ada pilihan lain. Kami harus mendaki cepat dan aman. Peralatan yang baik jadi salah satu jaminan keamanan,” kata Didiek.
Norman dan Deddy menyusul mereka ke Anchorage, dan langsung ke Talkeetna. Siap-siap sebentar dan terbang lagi ke Kahiltna Glacier. Cepat memang, tapi bukannya berlangsung mulus. Rudi Badil, teman dekat Norman bertanya pada saya, “Siapa lagi kali ini yang jadi ”korban” sasaran amukan Norman?”
“Korban” memang tidak ada. Namun bukan berarti ia tidak keras. “Di lapangan ia kerasnya minta ampun. Untung kita-kita sudah hapal kelakuannya. Toh dia berlaku keras untuk kebaikan tim juga,” kata Sute yang entah kenapa jadi orang yang paling lemah kondisinya. Artinya ia jadi orang yang paling sering didorong-dorong semangatnya untuk tetap mendaki.
“Saya sempat diberi pilihan tidak enak oleh Norman. Bisa ikuti kecepatan yang lain sampai ke puncak McKinley atau menjaga kemah. Mungkin karena pilihan yang sulit seperti itu, semangat justru bangkit,” lanjut Sute.
Norman sendiri bukan tanpa cacat. Ia sempat panik waktu memanjat tebing es dengan kemiringan 75 derajat di atas Windy Corner, 3.930 meter. Crampoon-nya sering kali lepas. Dan memanjat tebing es tanpa crampoon sama seperti mengais pasir tanpa jari.
Bayangkan kondisinya waktu itu. Ia ada di tebing es, membungkuk membetulkan crampoon dan menahan beban 40 kilogram di punggungnya. “Perbedaharaan makian joroknya terlontar semua,” komentar Deddy.
Langkah-langkah akhir ke puncak McKinley mulai ditapakkan. Semuanya tampak beres. Tebing terjal Denali Pass di ketinggian 5.547 meter dirayapi dalam waktu dua jam. Dari atas, piramida puncak McKinley memanggil-manggil. Tapi terlihatnya tak lama, sebab kabut dan angin kencang segera menutupinya. Suhu langsung meluncur turun ke titik 25 di bawah nol derajat Celcius. Down Jacket harus segera dipakai.
Dua ratus meter menjelang puncak, Didiek menengok ke arah puncak Utara. Antara percaya dan tidak, terlihat sosok mengenakan jacket parka merah melambai-lambai. Dia memberitahu Norman, “Man, ada orang di Puncak Utara.”
Norman juga melihat tapi ia membisu dan mendaki terus. Deddy dan Sute yang ikut mendengar ucapan Didiek menyanggah. Didiek akhirnya terdiam dan melangkah terus. Soal sosok misterius ini tetap jadi misteri sampai mereka kembali.
Di dekat puncak, Norman diam. “Hampa banget waktu itu. Emosi gue hilang. Yang ada hanya keinginan sampai (puncak) dan kembali,” begitu ia menceritakan pikirannya waktu itu. McKinley, titik tertinggi di Amerika Utara setinggi 6.194 meter, pun akhirnya bisa dijejaki.
Bendera-bendera yang wajib diabadikan dikeluarkan satu per satu. Wajah-wajah di balik goggles menahan mual. Norman terserang kantuk hebat. Penyakit ketinggian sedang hebat-hebatnya menyerang. Untunglah mereka tahan. Terakhir, seperti ditulis Didiek di catatan hariannya: “Kami harus turun, karena masih ada puncak-puncak lain yang harus didaki.”