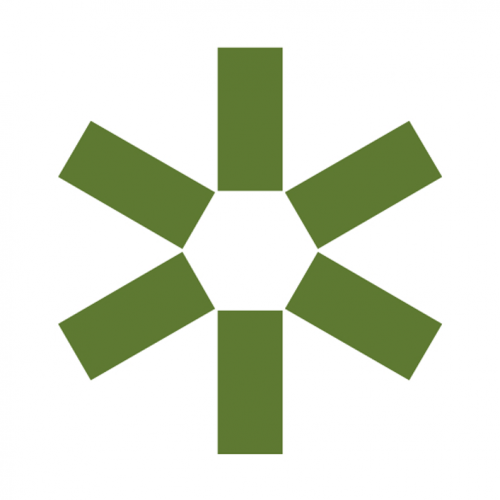Kakek itu masih berjalan dengan tegapnya mendaki ke arah kawasan hutan di atas bukit desanya. Di beberapa titik ia berhenti dan menyapa beberapa pria yang sedang bekerja di pembibitan pohon. Sampai di jalan masuk hutan, ia berhenti dan duduk di atas pipa yang mengalirkan air dari tiga sumber di Hutan Adat Wonosadi.

©2010
Cucunya yang sejak tadi mengiringi mengambil tempat tak jauh darinya. Sepilah bambu sejengkal tangan dikeluarkan, dipegang di depan mulutnya dan ditarik berbareng dengan hembusan getaran udara dari rongga mulut. Sang kakek meningkahi dengan denting senar-senar yang membujur di atas sebatang bambu bulat. Tak lama kemudian menggaung suara eksotik di dalam hutan dari duet kakek-cucu. Sang kakek menembang dengan syahdu.
Alat musik yang bernama rinding itu hanya salah satu dari upaya Sudiyo, sang kakek, untuk melestarikan alam dan budaya desanya. Upaya pelestarian lainnya adalah hutan itu sendiri. Hutan yang diberi nama Hutan Adat Desa Wonosadi itu membentang seluas 25 hektar, rimbun kukuh di perbukitan batas desa.
Melihat topografinya, hutan ini memang layak dilestarikan. Tingkat kemiringannya pun mengisyaratkan terjadinya erosi, bahkan ancaman tanah longsor apabila tak ada pepohonan rimbun yang menyerap dan menampung air hujan. Bencana bukan tak pernah singgah di Wonosadi,“Tahun 1964-1965 hutan ini gundul sebanyak 99 persen. Mata air mati, terjadi erosi, banjir kerikil dari gunung,” kenang Sudiyo.
Sudiyo mengakui bahwa kondisi politik masa itulah yang menjadi salah satu pendorong rusaknya hutan Wonosadi. ”Waktu itu kan pamong desanya kan ketua PKI. Lurah juga orang PKI, dia bilang,’itu kan hutanmu, di-tegori (tebangi-red) aja kalau butuh.’ Waktu itu politiknya PKI kan membodohi masyarakat agar miskin. Kalau sudah miskin harta, miskin pengetahuan, kan mudah dipengaruhi.”
Waktu itu Sudiyo sudah menjadi guru selama 6 tahun. Walaupun dipandang cukup berpendidikan, ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dominasi kekuatan politik PKI waktu itu. ”Saya juga takut,” akunya.
Selewat tahun 1965, lurah desa dijabat seorang polisi, saat itulah ia meminta Sudiyo yang dianggap sebagai seorang muda yang berpengetahuan untuk memulihkan hutan Wonosadi. Selain dipandang berpengetahuan seorang Sudiyo muda juga dipandang pantas karena keluarganya turun temurun menjadi juru kunci hutan itu.
”Setelah saya memulihkan hutan tahun 1966, lalu masyarakat kami kerahkan untuk menanam pada musim penghujan menanam kayu-kayuan dalam hutan, kayu apa saja, dengan syarat tidak boleh mematikan tumbuhan kayu yang tumbuh dengan sendirinya,” kenangnya.
Masyarakat desa menuruti ajakan Sudiyo. Tentunya menanami hutan kembali tidak bisa segera terlihat hasilnya. Mereka bekerja bersama hingga tahun 1969 terlihat pohon-pohon mulai tumbuh lagi. Pohon kayu semacam pohon jati (tectona grandis), pohon sengon (albizia falcataria), pohon johar (senna siamea) dan pohon mahoni (swietenia macrophylla) mereka tanam. Selain menanam baru, pokok-pokok tegakan pohon di hutan yang masih ada seperti pohon gondang (keluarga beringin, ficus variegata) dan pohon sengkek dibiarkan tumbuh.
Diakui oleh Sudiyo, masyarakat desa mengikuti ajakannya bukan karena pertimbangan lingkungan semata. Masalah kepercayaan juga menjadi latar belakang keinginan mereka memperbaiki Hutan Wonosadi. Mereka percaya orang-orang PKI yang tertumpas pada tahun 1965 itu sebagian disebabkan karena tingkah laku menebang hutan serampangan.
Ada cerita pula bagaimana sebuah keluarga melanggar pantang untuk menebang kayu di musim kemarau untuk membuat rumah. Rumah yang mereka bangun lalu terbakar. ”Itu karena kekuatan gaib,” yakin Sudiyo.
Kekuatan gaib itu diyakininya bisa selaras juga dengan ajaran religi. Seperti keimanan yang meyakini bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi, disepakati oleh Sudiyo.”Kalau menguasai alam untuk hidup itu tidak apa-apa. Misalnya tumbuhan untuk dimakan ya boleh dilakukan. Tapi bagi tumbuhan yang memastikan kelanjutan hutan ya tidak boleh. Kalau lebih banyak merusaknya seperti menebang hutan dan tumbuhan hingga mengeringkan mata air itu kan memutus hidup namanya. Sebagai khalifah di dunia, manusia itu harus memelihara daripada ciptaan Tuhan, iya toh?”
Pandangan lain soal hutan dan alam oleh Sudiyo adalah posisi kita sebagai pelaku di tengah jaman. Dari generasi sebelumnya kita mengusung amanat orang tua, bagi generasi berikutnya kita dititipi sumber daya itu agar bisa dimanfaatkan oleh anak cucu.
Posisi terhadap generasi sebelumnya dijabarkan olehnya,”Sopo sing urip-urip –siapa yang memelihara–? Orangtua, maka taatilah mereka. Seperti menjaga hutan ya taatilah, jangan dirusak hutannya orangtua. Orang jawa bilang mikul dhuwur mendem jero, menjunjung tinggi contoh yang baik dari orang tua dan menguburkan dalam-dalam hal yang kurang baik.”
Ia juga meyakini tanggung jawab berikutnya,”bahwa hutan ini bukan hutan kita tapi titipan anak cucu, ini tertulis di dalam aturan soal hutan ada Wonosadi. Dalam agama, kalo mati hanya membawa 3 hal. Pertama, ibadah. Kedua, ngamal. Kita buat hutan kan beramal buat anak cucu. Ketiga, kiriman anak cucu. Kiriman itu apa? Ya doa dari anak cucu. Kalau kita membuat hutan, kita mendapat ucapan terimakasih dari anak cucu. Anak cucu kita ingat, ’untung si mbah dulu membuat hutan.”
Keyakinan-keyakinan itu ditularkannya ke masyarakat desa. Tidak dengan model menggurui, tetapi dengan –istilah Sudiyo– nggonceng alias menumpang. Di desa yang masih kental dengan peristiwa-peristiwa komunal dimanfaatkannya. Misalnya ada rapat dusun atau upacara orang habis melahirkan atau kematian, mereka jagongan –berkumpul sambil berbincang–. Untuk berbincang mengenai pelestarian hutan, Sudiyo memulainya dengan pertanyaan sederhana. Apakah ada sesuatu yang buat kita lakukan untuk anak cucu?
bersambung…
Notes: ini adalah seri profil bersambung untuk buku mengenai Kehati Award.